Pengertian Inkomtabilitas ABO
Inkompatibilitas
ABO merupakan suatu kondisi sebagai akibat dari ketidaksesuaian
golongan darah antara ibu dan janin yang dikandungnya. (Ann Longsdon,
2012). Kondisi inkompatibilitas terjadi pada perkawinan yang
inkompatibel di mana darah ibu dan bayi yang mengakibatkan zat anti dari
serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit bayi dalam
kandungan. Sehingga
tidak jarang embrio hilang pada waktu yang sangat awal secara misterius
atau tiba-tiba, bahkan sebelum ibu menyadari bahwa ia hamil (Suryo, 2005).
Inkompatibilitas ABO merupakan salah satu penyebab dari penyakit hemolitik pada
neonatus yang biasanya terjadi pada janin dengan golongan darah A,B
atau AB dari ibu yang bergolongan darah O, karena antibodi yang
ditemukan pada golongan darah O ibuadalah dari kelas IgG yang dapat
menembus plasenta (Wagle, 2010).
Etiologi
Inkompabilitas ABO pada Kesalahan Tranfusi Darah
Kasus
hemolitik akibat inkompatibilitas ABO disebabkan karena ketidaksesuaian
golongan darah antara penerima dan pendonor. Ketidaksesuaian ini
mengakibatkan adanya reaksi penghancuran pada sel darah merah donor oleh
antibodi penerima. Keadaan ini disebut lethal tranfusion reaction
(Joyce Poole, 2001)
Keadaan
ini terjadi karena kurang hati-hati dan teliti dalam memberikan transfusi darah
pada:
- Golongan A, B, atau AB kepada penerima yang bergolongan darah O
- Golongan darah A atau AB kepada penerima yang bergolongan darah B
- Golongan darah B atau AB kepada penerima yang bergolongan darah A (Joyce Poole, 2001)
Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)
Kasus hemolitik akibat inkompatibilitas ABO
disebabkan oleh ketidakcocokan dari golongan darah ibu dengan golongan darah
janin, dimana umumnya ibu bergolongan darah O dan janinnya bergolongan darah A,
atau B, atau AB. Dikarenakan dalam kelompok golongan darah O, terdapat antibodi
anti-A dan anti-B (IgG) yang muncul secara natural, dan dapat melewati sawar
plasenta. Situasi ini dapat juga disebabkan oleh karena robekan pada membran
plasenta yang memisahkan darah maternal dengan darah fetal, sama halnya seperti
pada previa plasenta, abruptio placenta, trauma, dan amniosentesis. (Joyce
Poole, 2001)
Inkompabilitas pada Kesalahan Tranfusi Darah
Awal manifestasi klinis umumnya tidak spesifik, dapat berupa demam menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul, sesak napas, hipotensi, hiperkalemia, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan (hemoglobinuria). Pada reaksi hemolitik akut yang terjadi di intravaskular dapat timbul komplikasi yang berat berupa disseminated intravascular coagulation (DIC), gagal ginjal akut (GGA), dan syok (Joyce Poole, 2001).
Pada reaksi hemolitik tipe lambat memunculkan gejala dan tanda klinis reaksi timbul 3 sampai 21 hari setelah transfusi berupa demam yang tidak begitu tinggi, penurunan hematokrit, peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi, ikterus prehepatik, dan dijumpainya sferositosis pada apusan darah tepi. Beberapa kasus reaksi hemolitik tipe lambat tidak memperlihatkan gejala klinis, tetapi setelah beberapa hari dapat dijumpai DAT yang positif. Haptoglobin yang menurun dan dijumpainya hemoglobinuria dapat terjadi, tetapi jarang terjadi GGA. Kematian sangat jarang terjadi, tetapi pada pasien yang mengalami penyakit kritis, reaksi ini akan memperburuk kondisi penyakit (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).
Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)
Manifestasi yang ditimbulkan Inkompatibilitas ABO neonatus terhadap janin bervariasi mulai dari ikterus ringan dan anemia sampai hidrops fetalis. Manifestasi yang muncul pada bayi setelah persalinan meliputi :
Manifestasi Klinis
Awal manifestasi klinis umumnya tidak spesifik, dapat berupa demam menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul, sesak napas, hipotensi, hiperkalemia, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan (hemoglobinuria). Pada reaksi hemolitik akut yang terjadi di intravaskular dapat timbul komplikasi yang berat berupa disseminated intravascular coagulation (DIC), gagal ginjal akut (GGA), dan syok (Joyce Poole, 2001).
Pada reaksi hemolitik tipe lambat memunculkan gejala dan tanda klinis reaksi timbul 3 sampai 21 hari setelah transfusi berupa demam yang tidak begitu tinggi, penurunan hematokrit, peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi, ikterus prehepatik, dan dijumpainya sferositosis pada apusan darah tepi. Beberapa kasus reaksi hemolitik tipe lambat tidak memperlihatkan gejala klinis, tetapi setelah beberapa hari dapat dijumpai DAT yang positif. Haptoglobin yang menurun dan dijumpainya hemoglobinuria dapat terjadi, tetapi jarang terjadi GGA. Kematian sangat jarang terjadi, tetapi pada pasien yang mengalami penyakit kritis, reaksi ini akan memperburuk kondisi penyakit (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).
Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)
Manifestasi yang ditimbulkan Inkompatibilitas ABO neonatus terhadap janin bervariasi mulai dari ikterus ringan dan anemia sampai hidrops fetalis. Manifestasi yang muncul pada bayi setelah persalinan meliputi :
1) Asfiksia
2) Pucat (oleh karena
anemia)
3) Distres pernafasan
4) Jaundice
5) Hipoglikemia
6) Hipertensi pulmonal
7) Edema (hydrops,
berhubungan dengan serum albumin yang rendah)
8) Koagulopati (penurunan
platelets dan faktor pembekuan darah)
9)
Ikterus mengarah pada Kern ikterus oleh karena hiperbilirubinemia
(University of Califorrnia, 2004).
Patofisiologi
Inkompatibilitas ABO pada transfusi darah
Terjadinya inkompatibilitas ABO pada transfusi darah
disebabkan karena kesalahan transfusi yaitu kesalahan dalam pemberian darah
dimana golongan darah resipien berbeda dengan golongan darah pendonor. Hal ini
mengakibatkan antibodi didalam golongan darah resipien akan melisiskan sel
darah merah yang inkompatibel. Reaksi
hemolitik pada kejadian inkompatibilitas ABO dapat terjadi secara akut dan
secara lambat(Rizky Adriansyah, 2009).
Reaksi hemolitik akut pada transfusi merupakan masalah
yang serius karena terjadi destruksi eritrosit donor yang sangat cepat ( kurang
dari 24 jam ). Pada umumnya dikarenakan kesalahan dalam mencocokan sample darah
resipien dan donor. Proses hemolitik terjadi di dalam pembuluh darah
(intravaskular), yaitu sebagai reaksi hipersensitivitas tipe II. Plasma donor
yang mengandung eritrosit dapat merupakan antigen yang berinteraksi dengan
antibodi pada resipien berupa IgM anti-A, anti –B atau anti-Rh. Proses hemolitik
dibantu oleh reaksi komplemen sampai
terbentuk membran attack complex.
Pada beberapa kasus terjadi interaksi plasma donor sebagai antibodi dan
eritrosit resipien sebagai antigen. Pada reaksi hemolitik akut juga dapat
melibatkan IgG dengan atau tanpa melibatkan komplemen, dan proses ini dapat
terjadi secara ekstravaskular. Ikatan antigen dan antibodi akan meningaktivasi
reseptor Fc dari sel sitotoksik atau sel K yang menghasilkan perforin dan
mengakibatkan lisis dari eritrosit(Rizky Adriansyah,
2009).
Reaksi hemolitik lambat pada transfusi diawali dengan reaksi
antigen-antibodi yang terjadi di intravaskular, namun proses hemolitik terjadi
secara ekstravaskular. Plasma donor yang mengandung eritrosit merupakan antigen
yang berinteraksi dengan IgG atau C3b pada resipien. Selanjutnya eritrosit yang
telah diikat IgG dan C3b akan dihancurkan oleh makrofag di hati. Jika eritrosit
donor diikat oleh antibodi (IgG1 atau IgG3) tanpa melibatkan komplemen, maka
ikatan antigen-antibodi tersebut akan dibawa oleh sirkulasi darah
dandihancurkan di limpa (Rizky Adriansyah, 2009).
Inkompatibilitas
ABO pada Neonatus
Timbulnya penyakit Rh dan ABO pada neonatus
terjadi ketika sistem imun ibu
menghasilkan antibodi yang melawan sel darah merah pada janin yang
dikandungnya. Pada saat ibu hamil, eritrosit janin dalam beberapa insiden dapat
masuk kedalam sirkulasi darah ibu yang dinamakan Fetomaternal Microtransfusion. Bila ibu tidak memiliki antigen
seperti yang terdapat pada eritrosit janin, maka ibu akan distimulasi untuk
membentuk imun antibodi. Imun antibodi tipe IgG tersebut dapat melewati plasenta dan kemudian masuk kedalam peredaran darah janin sehingga sel-sel eritrosit janin akan diselimuti dengan antibodi tersebut dan akhirnya terjadi aglutinasi dan hemolisis, yang kemudian akan menyebabkan anemia. Hal ini akan dikompensasi oleh tubuh bayi dengan cara memproduksi dan melepaskan eritroblas (yang berasal dari sumsum tulang) secara berlebihan.Produksi eritroblas yang berlebihan dapat menyebabkan pembesaran hati dan
limpa yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya hepar dan ruptur limpa. Produksi eritroblas ini melibatkan berbagai komponen sel-sel darah, sepertiplatelet dan faktorpenting lainnya untuk pembekuan darah. Pada saat berkurangnya faktor pembekuan dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang banyak dan dapat memperberat komplikasi.
membentuk imun antibodi. Imun antibodi tipe IgG tersebut dapat melewati plasenta dan kemudian masuk kedalam peredaran darah janin sehingga sel-sel eritrosit janin akan diselimuti dengan antibodi tersebut dan akhirnya terjadi aglutinasi dan hemolisis, yang kemudian akan menyebabkan anemia. Hal ini akan dikompensasi oleh tubuh bayi dengan cara memproduksi dan melepaskan eritroblas (yang berasal dari sumsum tulang) secara berlebihan.Produksi eritroblas yang berlebihan dapat menyebabkan pembesaran hati dan
limpa yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya hepar dan ruptur limpa. Produksi eritroblas ini melibatkan berbagai komponen sel-sel darah, sepertiplatelet dan faktorpenting lainnya untuk pembekuan darah. Pada saat berkurangnya faktor pembekuan dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang banyak dan dapat memperberat komplikasi.
Hemolisis yang berat
biasanya terjadi oleh adanya sensitisasi maternal sebelumnya, misalnya karena
abortus, ruptur kehamilan di luar kandungan, amniosentesis, transfusi darah
Rhesus positif atau pada kehamilan kedua dan berikutnya. Penghancuran sel-sel
darah merah dapat melepaskan pigmen darah merah (hemoglobin), yang mana bahan
tersebut dikenal dengan bilirubin. Bilirubin secara normal dibentuk dari
sel-sel darah merah yang telah mati, tetapi tubuh dapat mengatasi kekurangan
kadar bilirubin dalam sirkulasi darah pada suatu waktu. Eritroblastosis fetalis
menyebabkan terjadinya penumpukan bilirubin ,yang dapat menyebabkan
hiperbilirubinemia, yang nantinya menyebabkan jaundice pada bayi. Bayi dapat
berkembang menjadi kernikterus.
Komplikasi
Inkompabilitas pada Kesalahan Tranfusi Darah
Dalam kasus ini penderita dapat mengalami
masalah yang serius hingga kematian. Penatalaksanaan yang tepat dapat
menyelamatkan jiwa penderita. Komplikasi yang mungkin muncul pada
inkompatibilitas ABO sebagai akibat reaksi tranfusi adalah gagal ginjal, syok anafilaktik,
dan kematian (Rizky Adriansyah, et.al., 2009)
Inkompabilitas pada Kondisi Kehamilan (Neonatus)
Apabila janin sampai aterm dilahirkan hidup maka
dapat terjadi ikterus yang dapat mengarah pada ikterus patologis atau
hiperbilirubinemia. Apabila hal ini tidak ditangani secara tepat dapat
menimbulkan kematian atau kelainan perkembangannya seperti gangguan
perkembangaan mental, tuli, lambat bicara dan lain-lain (Suryo, 2005).
Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang pada inkompatibilitas ABO kesalahan
tranfusi
a. Pemeriksaan
crossmatch ulang antara darah
pendonor dan penerima
b. Direct
Antiglobulin Test (DAT)
c. Pemeriksaan
serologis rhesus
d. Urinalisis
didapatkan adanya hemoglobinuria
e. Pemeriksaan
lain untuk mengetahui komplikasi dari reaksi hemolitik, antara lain:
- Renal
function test
- LDH,
bilirubin dan haptoglobin
- Status koagulasi (prothrombin time, partial thromboplastin time, dan
fibrinogen) (Rizky Adriansyah, et.al., 2009).
Pemeriksaan penunjang pada Inkompatibilitas ABO
neonatus, meliputi:
a.
Pemeriksaan Klinis
Pemeriksaan
klinis neonatus pada kasus inkompatibilitas ABO merujuk pada pemeriksaan klinis
pada ikterus neonatorum karena secara klinis neonatus dengan inkompatibilitas
ABO akan mengalami ikterus/ hiperbilirubinemia. Ikterus/ hiperbilirubinemia
adalah pewarnaan di kulit, konjungtiva, dan mukosa yang terjadi karena
meningkatnya kadar bilirubin dalam darah (Djoko Waspodo et.al., 2005)
Klinis
akan menunjukkan ikterus bila kadar bilirubin dalam serum adalah ≥ 5mg/dl
(85µmol/L). Disebut hiperbilirubin adalah keadaan kadar bilirubin serum
mencapai 13 mg/dl (Djoko Waspodo et.al., 2010).
Pemeriksaan klinis ikterus dilakukan menggunakan pencahayaan yang
memadai. Pemeriksaan dimulai dari kepala, leher, dan seterusnya. Cara
pemeriksaannya ialah dengan menekan jari telunjuk di tempat yang tulangnya
menonjol seperti tulang hidung, tulang dada, lutut dan lain-lain. Kemudian
penilaian kadar bilirubin dari tiap-tiap nomor disesuaikan dengan angka
rata-rata di dalam gambar di bawah ini :
Pemeriksaan tanda klinis lain, meliputi adanya
gangguan minum, keadaan umum, apnea, suhu yang labil, sangat membantumenegakkan
diagnosa penyakit utama disamping keadaan hiperbilirubinemianya (Djoko Waspodo
et.al., 2010).
a.
Hitung sel darah merah
Pada
kasus inkompatibilitas ABO pada neonatus, pemeriksaan sel darah merah
menunjukkan adanya retikulositosis (retikulosit > 4, 6%) dan mikrosferosit
pada hapusan darah tepi (Desiana Dharmayani, et.al., 2009)
Retikulosit
merupakan sel darah merah imatur. Jika terjadi anemia, sumsum tulang berusaha mengkompensasi
dengan meningkatkan aktivitas eritropoiesis, yang tercermin pada peningkatan
hitung retikulosit. Jika produksi sumsum tulang terganggu maka hitung
retikulosit akan tetap rendah (Desiana Dharmayani, et.al., 2009).
b.
Direct Coomb Test (DCT)
Neonatus yang mengalami inkompatibilitas ABO, menunjukkan hasil positif
pada pemeriksaan ini. Tujuan dari pemeriksaan DCT
untuk mengetahui apakah sel darah merah diselubungi oleh IgG atau komplemen,
artinya apakah ada proses sensitisasi pada sel darah merah di invivo (pada
tubuh pasien). Bahan yang dipergunakan adalah sel darah merah pasien. Pada
pemeriksaan ini menggunakan sampel darah dengan antikoagulan EDTA (Desiana
Dharmayani, et.al., 2009).
Penatalaksanaan
Inkompabilitas ABO pada Kesalahan Tranfusi
1.
Pemberian tranfusi harus
diberhentikan
2.
Pemberian cairan
intravena dilakukan
dengan hidrasi PZ (3000ml/m2/hari)
3.
Untuk pencegahan GGA :
a.
Dapat diberikan dopamin
dosis rendah 1-5 mcg/kg/menit
b.
Diuretik osmotik: manitol
(100 ml/kg/hari), selanjutnya diberikan 30ml/kg/hari atau furosemid 1-2ml/kgBB
Jika dijumpai tanda DIC, pertimbangkan untuk dilakukan tranfusi FFP,
kriopresipitat, dan/ atau trombosit (Rizky
Adriansyah, et.al., 2009).
Inkompabilitas ABO pada Kondisi Kehamilan
(Neonatus)
1.
Tatalaksana pada
inkompatibilitas ABO dengan ikterus fisiologis
di rumah adalah :
a.
Anjurkan ibu untuk
menyusui bayi secara dini, dan ASI eksklusif lebih sering minimal tiap 2 jam.
b.
Jika bayi tidak dapat
menyusu, ASI eksklusif dapat diberikan melalui pipa nasogastrik atau dengan
gelas dan sendok
c.
Gendong bayi untuk
mendapatkan sinar matahari pagi selama 30 menit pada pukul 07.00-07.30 WIB,
dalam 3-4 hari (Tunjung Wibowo, 2010)
d.
Pada dasarnya
inkompatibilitas ABO dengan ikterus fisiologis tidak memerlukan penanganan
khusus dan dapat menjalani rawat jalan dengan nasehat untuk kembali jika
ikterik berlangsung lebih dari 2 minggu (Djoko Waspodo et.al., 2010)
2.
Pemberian fototerapi
Fototeraapi merupakan terapi yang dilakukan dengan
menggunakan cahaya dari lampu fluorescent khusus dengan intensitas tinggi,
secara umum metode ini efektif untuk mengurangi serum bilirubin dan mencegah
ikterus (Potts and Mandleco, 2007).
Fototerapi dilakukan dengan memberikan sinar ultraviolet,
baik sinar biru (δ 400-550 nm), sinar hijau (550-800nm) maupun sinar putih
(300-800 nm) akan mengubah bilirubin indirek menjadi bentuk yang larut dalam
air untuk diekskresikan melalui empedu atau urin dan tinja. Sewaktu bilirubin
mengabsorpsi cahaya, terjadi reaksi kimia yaitu isomerisasi, selain itu
terdapat juga konversi ireversibel menjadi isomer kimia lainnya yang disebut
lumirubin yang secara cepat dibersihkan dari plasma saluran empedu. Lumirubin
merupakan produk terbanyak dari degradasi bilirubin akibat terapi sinar
(fototerapi). Sejumlah kecil bilirubin plasma tak terkonjugasi diubah oleh
cahaya menjadi dipyrole yang diekskresikan lewat urin. Hanya produk foto oksidan saja
yang dapat diekskresikan melalui urin (Ali Usman, 2007).
Foto terapi menggunakan bola lampu sejumlah 6-8 buah,
terdiri dari biru (F20T12), cahaya biru khusus (F20T12/BB) atau
daylightfluorescent tubes (Porter and Dennis, 2002). Spektrum cahaya yang
dikirim oleh unit fototerapi ditentukan oleh tipe sumber cahaya dan filter yang
digunakan, biasanya terdiri dari daylight, cool white, blue atau special
bluefluorescent tubes dan diberi label F20T12/BB atau TL 52/20W. Durasi
fototerapi dihitung berdasarkan waktu dimulainya fototerapi sampai fototerapi
dihentikan. Durasi fototerapi ditentukan oleh penurunan nilai total serum
bilirubin sampai mencapai nilai yang diharapkan, sehingga tidak ada penentuan
berapa jam sebaiknya fototerapi diberikan
(American Academy of Pediatric, 2004).
Fototerapi diberikan pada bayi yang mengalami
ikterus berat, kemudian tentukan apakah bayi memiliki faktor resiko, seperti:
BBLR, preterm, dan hemolisis. Hentikan fototerapi jika bilirubin serum berada
di bawah nilai dibutuhkannya terapi sinar, akan tetapi jika bilirubin serum
berada pada atau di atas nilai yang dibutukan terapi sinar, maka lanjutkan
fototerapi Pengukuran kadar bilirubin dilakukan tiap 24 jam,
kecuali pada kasus-kasus tertentu. Fototerapi dihentikan jika kadar bilirubin
serum kurang dari 13mg/dL. Jika kadar bilirubin tidak dapat diukur, lanjutkan
sampai 3 hari kemudian dan lakukan pemeriksaan bilirubin serum jika
memungkinkan. Akan tetapi jika tetap tidak bisa dilakukan pemeriksaan bilirubin
serum, maka lakukan pemeriksaan ikterus dengan metode klinis (Moeslichan, et.al., 2004; American Academy of Pediatric, 2004).
Dosis dan kemanjuran dari fototerapi biasanya
dipengaruhi oleh jarak antara lampu (semakin dekat sumber cahaya, semakin besar
irradiasinya) dan permukaan kulit yang terkena cahaya, karena itu dibutuhkan
sumber cahaya di bawah bayi pada fototerapi intensif (Maisels,et al, 2008).
Jarak antara kulit bayi dan sumber cahaya. Dengan lampu neon, jarak harus tidak
lebih besar dari 50 cm (20 inch). Jarak ini dapat dikurangi sampai 10-20 cm
jika homeostasis suhu dipantau untuk mengurangi resiko overheating (Judarwanto,
2012).
Efek samping ringan yang harus diwaspadai
perawat meliputi feses encer kehijauan, ruam kulit transien, hipertermia,
peningkatan kecepatan metabolisme,seperti hipokalsemia dan priaspismus. Untuk
mencegah atau meminimalkan efek tersebut, suhu dipantau untuk mendeteksi tanda
awal hipotermia atau hipertermia, dan kulit diobservasi mengenai dehidrasi dan
kekeringan, yang dapat menyebabkan ekskoriasi dan luka (Wong, 2009).
Komplikasi terapi sinar umumnya ringan, jarang
terjadi dan reversibel. Komplikasi yang sering terjadi (Sastroasmoro, 2004) :
a)
Bronze
baby sindrom : mekanisme berkurangnya ekresi hepatic hasil penyinaran bilirubin
b) Diare : bilirubin indirek menghambat laktase
c) Hemolisis : fotosensitivitas mengganggu sirkulasi eritrosit
d) Dehidrasi : Insesible Water Loss ↑ (30-100%) karena menyerap energi
foton.
e) Ruam kulit : Gangguan
fotosensitasi terhadap sel mast kulit dengan
pelepasan histamin.
Peran perawat dalam pelaksanaan fototerapi
sebagai berikut :
a)
Mengusahakan tubuh bayi terpapar sinar seluas mungkin, bila perlu bukalah
pakaian bayi
b)
Menutup kedua mata dan gonad dengan penutup yang memantulkan cahaya untuk
melindungi sel-sel retina dan mencegah gangguan maturasi seksual.
c)
Meletakkan bayi 50 cm (20 inch) di bawah sinar lampu untuk mendapat energi
cahaya yang optimal
d)
Mengubah posisi bayi setiap 2-4 jam.
e)
Memotivasi ibu untuk tetap menyusui bayinya tiap 3 jam sekali, jika bayi
menerima cairan melalui intravena/makanan melalui NGT maka jangan memindahkan
bayi.
f)
Mengukur suhu bayi setiap 3 jam sekali, jika suhu bayi >37,5°C maka atur
kembali suhu ruangan/pindahkan sementara suhu bayi sampai suhunya mencapai
36,5°C-37,5°C. Matikan sinar fototerapi jika
bayi sedang menerima oksigen (Mali, 2007).
g)
Mengkolaborasikan pemeriksaan kadar bilirubin sekurang-kurangnya sekali
dalam 24 jam
h) Observasi hidrasi bayi, bila
perlu tingkatkan konsumsi cairan bayi
i) Melakukan pencatatan terapi sinar
j) Buat asuhan keperawatan selama
bayi fototerapi
(Moeslichan, 2007)
3.
Pemberian tranfusi
albumin
4.
Tranfusi tukar
(darah)
Transfusi
tukar adalah suatu tindakan pengambilan sejumlah darah pasien dilanjutkan
dengan pengembalian darah dari donor dalam jumlah yang dilakukan berulang-ulang
sampai sebagian besar darah terpenuhi. Manfaat lebih tranfusi
tukar yaitu membantu mengeluarkan antibodi maternal dari sirkulasi darah
neonatus sehigga mencegah terjadinya hemolisis lebih lanjut dan memperbaiki
kondisi anemia.(Ali Usman, 2007). Ketentuan dalam tranfusi
tukar sebagai berikut :
a) Darah
donor yang digunakan tranfusi adalah golongan
O.
b) Gunakan
darah baru (usia < 7 hari), whole blood.
c)
Pada inkompatibilitas ABO,
darah donor harus golongan O,
d) Rhesus
(-) atau Rhesus yang sama dengan ibu atau bayinya. Cross match terhadap ibu dan
bayi yang mempunyai titer rendah antibodi anti A dan anti B. Biasanya memakai
eritrosit golongan O dengan plasma AB, untuk memastikan bahwa tidak ada
antibodi anti A dan anti B yang muncul.
Transfusi tukar memakai 2 kali volume darah (2 kali exchange), yaitu 160
ml/kgBB sehingga akan diperoleh darah baru pada bayi yang dilakukan transfusi
tukar sekitar 87% (Ali Usman, 2007).
5. Suplementasi zat gizi
Defisiensi zat besi pada neonatal disebabkan proses kehilangan darah
kronis/deplesi cepat cadangan zat besi yang jumlahnya terbatas. Defisiensi zat
besi terjadi lebih berat pada bayi prematur yang pertumbuhannya lebih cepat dan
cadangan zat besinya minimal. Oleh karena itu suplementasi zat besi diperlukan
untuk mendukung proses eritropoiesis yang efektif. Terapi utama adalah
mengatasi penyebab deplesi zat besi (misalnya kehilangan darah akut atau
kronis, masalah absorbsi) dan memberikan suplementasi dengan zat besi elemental
6 mg/kgBB/hari. (Sumber: Risalina Myrtha, 2014)
Konsep
Asuhan Keperawatan pada Inkompabilitas ABO
Pengkajian
1)
Data Demografi :
Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi, data
pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin,
Pada inkompabilitas ABO neonatus
meliputi data bayi (nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, agama,
suku bangsa, alamat) dan data orang tua (nama, usia, pendidikan, perkawinan,
pekerjaan, alamat, penghasilan, golongan darah)
2) Keluhan
Utama :
Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi,
meliputi : demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri pada panggul,
sesak napas, dan urin berwarna kemerahan atau keabuan.
Pada inkompabilitas ABO neonatus,
biasanya bayi dirawat karena kuning pada wajah dan seluruh tubuh lebih dari 1
hari, pucat, bengkak, dan sesak napas.
3) Riwayat
penyakit sekarang :
Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi :
kronologi tindakan tranfusi yang didapat sampai waktu muncul reaksi yang
dirasakan seperti demam, menggigil, dll setelah mendapat terapi tranfusi.
Pada inkompabilitas ABO neonatus :
kronologi munculnya kondisi kuning, sejak kapan, berapa lama, riwayat tindakan
yang diberikan dirumah samapai MRS.
4) Riwayat
Penyakit Dahulu :
Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi : riwayat
penyakit sebelunya yang diderita, indikasi tranfusi, riwayat MRS.
Pada neonatus meliputi
riwayat kehamilan dan persalinan serta
riwayat penyakit penyerta pada ibu.
5) Pemeriksaan Fisik
Pada inkompabilitas ABO kesalahan tranfusi meliputi :
A (Airway) :
Distress pernapasan
B
(Breathing) : RR meningkat (>20x/menit), sesak nafas
C
(Circulation) : Pasien menggigil,
sianosis, pucat, hipertermi, hipotensi.
B1
(Breathing) : Sesak nafas disebabkan
oleh spasme otot pernaffasan meningkat sehingga terjadi obstruksi, RR meningkat
(>20x/menit), pernafasan cuping hidung.
B2 (Blood) : Sianosis terjadi akiat penurunan
sirkulasi perifer, pucat, hipertermi, hipotensi, jika tidak teratasi
menyebabkan syok hipovolemik.
B3 (Brain) : Pada kondisi tidak teratasi
menyebabkan penurunan kesadaran.
B4 (Bladder) :
Oliguri, hematuria.
B5 (Bowel) : Mual dan muntah akibat reaksi alergi
antigen-antibodi.
B6 (Bone) : Pasien mengalami kelemahan.
Pada inkompabilitas neonatus meliputi :
a)
Kondisi umum :
menangis (kuat/tidak), gerakan (aktif/tidak)
b)
Kesadaran : compos
mentis/tidak
c)
Status
antropometri : BB, PB, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar abdomen, lingkar
lengan, apgar skor, TTV (Suhu,Nadi,RR)
d)
Pemeriksaan
Primary Survey
A (Airway) : Inkompatibilitas
pada kondisi kehamilan biasanya
menyebabkan asfiksia dan distress pernapasan
B (Breathing) : Distress pernapasan pada inkompatibilitas pada
kondisi kehamilan dan sesak napas pada
kondisi
kesalahan transfusi
C (Circulation) : Haemorrhage
control (Anemia, hipotensi,
Hemoglobinuria)
e)
Pemeriksaan Head
to Toe :
· Kepala :
normocepal, adakah caput, hematom, kondisi UUB, adakah jaundice
· Mata : sclera
ikterik
· Telinga : normal
· Hidung :
pernapasan cuping hidung, sesak napas
· Mulut : mukosa
kekuningan, lidah kuning
· Leher : normal
· Tenggorokan :
sulit terkaji (biasanya normal)
· Thorak : simetris,
retraksi dinding dada +, ikterik pada kulit dada, jantung normal, paru normal
·
Abdomen : tampak
cembung, ikterik pada kulit abdomen, turgor kulit baik, bising usus normal
· Ektremitas : gerakan,
akral, adanya ikterik, CRT normal (<2 detik)
· Kulit : berwarna
pucat (sianosis +), ikterik (bisa di seluruh tubuh)
Diagnosa
Keperawatan
Pada inkompatibilitas ABO Kesalahan Tranfusi :
- Gangguan perfusi jaringan perifer b.d gangguan transportasi oksigen
- Hipertermi b.d peningkatan metabolisme
- Gangguan perfusi jaringan serebral b.d gangguan transportasi oksigen di otak.
- Kelebihan volume cairan b.d penurunan mekanisme pengaturan urin.
- Kerusakan integritas kulit b.d gangguan kondisi metabolic.
- Risiko perdarahan b.d terjadinya fibrinolisis.
Pada inkompatibilitas ABO Kondisi Kehamilan (Ibu-Neonatus)
:
- Gangguan pertukaran gas b.d gangguan suplai oksigen dan ketidakseimbangan ventilasi
- Neonatal jaundice berhubungan dengan hiperbilirubinemia sekunder umur bayi kurang dari 7 hari
- Kerusakan integritas kulit b.d kondisi gangguan metabolik
- Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan.
- Kerusakan mobilitas fisik b.d gangguan metabolisme di otak.


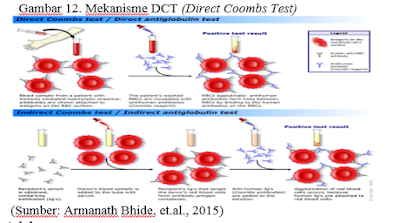

maaf sblmnya, ibu yg bergolongan O ngak mungkin anaknya ab
BalasHapusKalaupun suaminya ab, anaknya kalau ngak a ya b